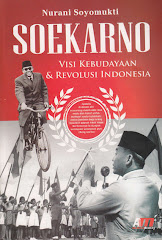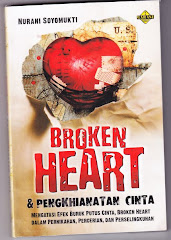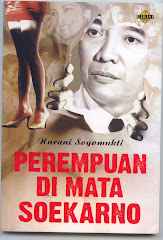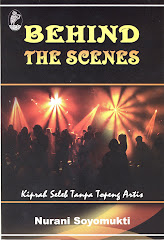(Hanya) Menjual Kecantikan!!!
Oleh Nurani
“Aku baru bangun tidur. Tadi mimpi meludahi muka Julia Perex, Dewi Bersisik, Dewi Tersandra, Asmirondho, Titi Kumal, Naysila Murtad, Maiyat Estianti, Marsandal, Mulan Jamahlah, dan Agnes Mounikah”.
(Sms dari Teman saya, Bejo)
“Wanita anggun jarang membuat sejarah”.
(Anita Borg)
“Cantik Itu Luka”.
(Eka Kurniawan, Sastrawan)
Esai ini bukan hanya riak-riak kecil dari bukuku yang akan terbit, “BEHIND THE SCENES” (Jakarta—Prestasi Pustaka, 2009), kisah tentang posisi selebritis dalam kapitalisme hiburan—(sebenarnya) juga dalam pertarungan kelas antara rakyat yang dimiskinkan dengan selebritis yang semakin pamer kemewahan dalam tatanan kapitalisme yang kian timpang!
 Esai ini hanyalah ungkapan sentimentil. Barangkali! Intinya, kita dituntut untuk berpikir secara filsafati untuk melihat berbagai ekspresi budaya dan mencari makna dari dialektika material yang sebenarnya…
Esai ini hanyalah ungkapan sentimentil. Barangkali! Intinya, kita dituntut untuk berpikir secara filsafati untuk melihat berbagai ekspresi budaya dan mencari makna dari dialektika material yang sebenarnya…
Julia Perex dan Dewi Bersisik
Seperti temanku Bejo, terus terang aku juga semakin muak dengan sederetan artis seperti Julia Perex, Dewi Bersisik, Luya Mana, Cinta Lora, dll, yang hanya mirip boneka bodoh yang menjual kecentilan. Maafkan aku dengan perasaan ini! Bagi kamu yang gak sependapat denganku, tidak apa-apa tak sepakat. Tapi aku punya pendapatku sendiri tentang nilai dan ukuran... ukuran tentang peran dan posisi seseorang yang hidup dalam pergulatan hidup di era kapitalisme ini. Aku terpaksa menilai mereka. Ya... karena mereka yang tiap hari ‘nongol’ di depan kita, berusaha menularkan nilai mereka.
Jadi sebut saja tulisan ini adalah perang nilai dan perang ideologi. Perang antara tulisan-tulisanku yang mendeligitimasi peran para enterteiner yang parasit dalam budaya borjuis-kapitalis, dengan mereka yang ingin menanamkan ideologi kapitalis melalui nilai-nilai secara terus-menerus. Media mereka TV, majalah gaul, cabul, dan yang agak cabul...
Nilai yang akan kudiskusikan adalah soal NILAI KECANTIKAN!
Model=Domba Tolol
Dewasa ini, kecantikan adalah nilai yang paling dipuja. Kontes kecantikan adalah salah satu contoh menyesatkan. Kontes ini membuat perempuan berpikir bahwa hal terpenting yang harus dikejar dala m hidup adalah menguasai tips kecantikan dan keahlian mencari jodoh. Lalu mereka menawarkan hadiah berupa beasiswa yang justru membuat keadaan sangat ironis karena para lelaki penonton acara kontes kecantikan itu rata-rata adalah penyuka perempuan yang bodoh. Menurut seorang pengamat relasi laki-laki-perempuan di Amerika, Serry Argov, kalau kita kritis sebenarnya kita akan perhatikan bahwa:
m hidup adalah menguasai tips kecantikan dan keahlian mencari jodoh. Lalu mereka menawarkan hadiah berupa beasiswa yang justru membuat keadaan sangat ironis karena para lelaki penonton acara kontes kecantikan itu rata-rata adalah penyuka perempuan yang bodoh. Menurut seorang pengamat relasi laki-laki-perempuan di Amerika, Serry Argov, kalau kita kritis sebenarnya kita akan perhatikan bahwa:
“kontes kecantikan itu mirip banget sama pameran hewan ternak. Para peternak itu memamerkan sapi-sapi mereka dengan cara yang sama dengan para kontestan kecantikan. Mereka menggiring sapi…juara mereka ke tengah panggung di depan penonton dan para juri, dan mungkin bahkan memerintahkan sapi mereka beraksi sedikit di tengah panggung menunjukkan kebolehannya. Lalu, sapi-sapi yang menang akan diberi pita satin dengan nama gelar yang diperoleh berikut tahunnya”.[1]
Banyak yang tentunya sepakat bahwa kemunduran perempuan salah satunya adalah karena kapitalisme-komersialisme yang membentuk cara berpikir kaum perempuan bahwa mereka hanya dapat menyandarkan eksistensi dirinya pada penampilan fisik. Sherry Argov melontarkan nasehat pada kaum perempuan ketika mereka ingin mendapatkan calon suami yang sejati:
“Ketika laki-laki melihat kamu memakai pakaian yang terbuka, biasanya ia [laki-laki] akan berasumsi bahwa kamu nggak punya hal lain yang menarik dalam diri kamu... Ketika dia [laki-laki] melihat kamu berpakaian sangat minim, dia nggak akana mengingat betapa rendahnya tubuh kamu yang telanjang itu. Tapi dia akan segera berpikir tentang berapa banyak laki-laki yang pernah berhubungan sama kamu”.[2]
Dalam hubungan kapitalistik, kepercayaan antara satu manusia satu dengan lainnya, termasuk antara laki-laki dan perempuan, semakin luntur karena kebanyakan orang frustasi akibat penind asan dan tekanan hidup hingga mereka semakin diracuni oleh pikiran bahwa satu-satunya hal yang dapat mewakili mereka dalam interaksi hanyalah modal dan ‘sesuatu’ yang dapat ditawarkan sebagaimana halnya transaksi dalam pasar.
asan dan tekanan hidup hingga mereka semakin diracuni oleh pikiran bahwa satu-satunya hal yang dapat mewakili mereka dalam interaksi hanyalah modal dan ‘sesuatu’ yang dapat ditawarkan sebagaimana halnya transaksi dalam pasar.
Ketika bertemu dengan perempuan bodoh yang hanya mengandalkan penampilan fisiknya, seorang laki-laki yang kaya mungkin akan berpikir: “Alah, apa arti kecantikanmu... dengan mudah aku dapat membelinya”—dengan membungkusnya dengan basa-basi perkawinan sang laki-laki pun bisa memiliki dan menguasai si perempuan cantik (bisa jadi perempuan ‘baik-baik’) di dalam rumah. Si perempuan sejak awal memang merasa mampu mendapatkan perlindungan dan keamanan finansial ketika mereka bisa menarik hati pria kaya. Pria kaya dan punya pengalaman kebebasan yang lumayan, mungkin sudah dapat menakhlukkan para perempuan lainnya tanpa harus menikah, dan dia tentu butuh seorang istri yang bisa diandalkan dirumah.
Sementara itu, tak sedikit kaum perempuan yang memang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan pria kaya dengan cara memelihara dan meningkatkan modal kecantikan fisiknya. Tak sedikit di antara mereka yang juga sadar bahwa mereka tak melibatkan perasaan cinta saat menikah, tetapi memang semata-mata mencari keamanan finansial dan menjadi ‘social climber’—perempuan yang ingin naik kelas dengan bermodalkan kecantikan tubuh.
Perempuan harus mempersiapkan kemampuan seolah ia ingin memiliki kapasitas yang dibutuhkan pria yang memang membutuhkan kepuasan seksual ketika berhubungan dengan perempuan. Seringkali perempuan dikasihtahu oleh majalah-majalah dan media bahwa untuk memenangkan hati laki-laki adalah lewat seks.
Jual Keliaran, Seperti (Julia) Pereks
Bacalah majalah-majalah atau buku-buku, misalnya artikel yang berjudul “100 Tips Seks yang Akan Membuatnya Liar”. Kebanyakan tulisan semacam itu sangatlah tolol dan benar-benar membuat perempuan tolol setelah membacanya. Para penulis artikel kacangan itu akan memberikan anjuran, misalnya: perempuan bisa membuat hubungan seks yang penuh petualangan yang membuatnya memberi kesan pada laki-laki sebagai ahli di ranjang. Contoh nasehat detail terhadap perempuan dari artikel semacam itu misalnya: Kamu selalu muncul dengan ‘lingerie’ yang bisa dimakan, goyangan seksual yang spektakuler, barang-barang berbahan lateks, akrobat di ranjang dengan borgol bulu-bulu, dan kamu juga bisa memasang lampu bola disko disamping ranjang agar kegiatan seksual romantis. Terus kamu mengikat tangan laki-laki, menyumpal mulut mereka dengan stocking-mu agar gairah seksual liar, dan memberi suara-suara atau lenguhan yang seksi seperti—misalnya—anjing menggonggong.
Hanya perempuan yang menyadari bahwa seks dan kecantikan bukanlah satu-satunya modal, yang akan menyadari potensi lain dari keberadaannya. Potensi itu adalah seluruh tubuhnya, terutama pikiran maju dan penuh wawasan yang akan mengendalikan tindakannya untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan baru. Perempuan semacam ini sadar bahwa dia juga harus mendapatkan ruang yang lapang untuk terus belajar dan berperan dalam masyarakanya.
Hidupn ya bukan hanya untuk mengurusi dirinya sendiri, misalnya hanya sibuk merekayasa penampilan agar banyak orang lain yang kagum terhadap dirinya hanya karena ia menonjol di bidang itu. Kita seringkali menjumpai perempuan yang bergelimang popularitas seperti perempuan artis-selebritis yang dikagumi banyak orang dan mendapatkan kepuasan individual dalam kehidupan hari-harinya, bahakn selalu mampu memenuhi kebutuhan individualnya dengan mudah dan hidup mewah. Kita bisa mengatakan bahwa perempuan semacam itu memiliki posisi di ruang publik karena ketenarannya, tetapi kebanyakan perempuan semacam itu sesungguhnya sama sekali tak dapat diandalkan dalam urusan publik yang serius, dengan kemampuan daya pikirnya yang terbatas dan dangkal.
ya bukan hanya untuk mengurusi dirinya sendiri, misalnya hanya sibuk merekayasa penampilan agar banyak orang lain yang kagum terhadap dirinya hanya karena ia menonjol di bidang itu. Kita seringkali menjumpai perempuan yang bergelimang popularitas seperti perempuan artis-selebritis yang dikagumi banyak orang dan mendapatkan kepuasan individual dalam kehidupan hari-harinya, bahakn selalu mampu memenuhi kebutuhan individualnya dengan mudah dan hidup mewah. Kita bisa mengatakan bahwa perempuan semacam itu memiliki posisi di ruang publik karena ketenarannya, tetapi kebanyakan perempuan semacam itu sesungguhnya sama sekali tak dapat diandalkan dalam urusan publik yang serius, dengan kemampuan daya pikirnya yang terbatas dan dangkal.
Lihatlah, tiap hari kita disuguhi lontaran-lontaran gampangan, dangkal, dan kacangan dari para perempuan penghibur semacam itu di acara infoteinmen (gosip) yang ditayangkan hampir setiap jam. Bahkan kalau mau jujur ungkapan-ungkapan mereka juga ikut mempelopori kemunduran cara pandang dan kesadaran kaum perempuan di maasyarakat—karena bagaimanapun mereka adalah tokoh publik. Apa yang diberikan bagi kesadaran perempuan untuk lepas dari penindasan dari mulut selebritis seperti Julia Perez, Dewi Persik, Agnes Monica, Cinta Laura dan lain-lainnya?
Hubungan Palsu
Oh, kayaknya saya terlalu menggambarkan perempuan-perempuan murahan yang berusaha direproduksi kapitalisme. Laki-laki yang membangun hubungan secara serius dengan perempuan memang tak suka ketika seorang perempuan bersikap terlalu artifisial, laki-laki bahkan resah dan kawatir tentang siapa dirinya sebenarnya dan apa motivasi serta tujuan perempuan itu. Biasanya, laki-laki akan berpikir bahwa semua yang dikenakan perempuan itu adalah untuk menjebaknya.
Tentu kita juga akan mengatakan bahwa laki-laki yang hanya memanfaatkan kelemahan perempuan adalah laki-laki yang tidak memiliki nilai yang dipegang dalam membangun hubungan. Karena dia hanya main-main, karena tak percaya pada nilai. Atau tak berusaha memperjuangkannya. Laki-laki kaya juga akan cenderung mewakili hubungannya dengan kekayaannya, artinya di situlah dia telah memanipulasi dirinya.
Kepemilikanlah yang menjadi wakil dari eksistensi dirinya. Ketika kualitasnya jelek, ia mengandalkan materi dan kepemilikannya untuk menarik orang lain agar mau berhubungan dengannya, terutama perempuan-perempuan yang begitu mudah tergoda dengan mater—perempuan-perempuan parasit yang tidak mandiri dan hanya mengandalkan perlindungan laki-laki dan orang lain.
Kecantikan yang dijual adalah seba-sebab retaknya hubungan rumahtangga. Suami-suami tanpa sepengetahuan istri, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangat tertarik dengan perempuan-perempuan yang lebih muda. Dan cara pandang laki-laki semacam itu tampaknya dipenuhi oleh kebutuhan pasar: dari acara yang paling ‘gaul’ hingga yang paling ilmiah sepert i seminar seakan harus menyediakan perempuan muda yang cantik dan seksi. Yang menginginkan bukan perempuan, tetapi jelas untuk memenuhi kebutuhan laki-laki yang ingin sekedar ‘cuci mata’ hingga mengajak perempuan-perempuan SPG yang mau diajak kencan itu.
i seminar seakan harus menyediakan perempuan muda yang cantik dan seksi. Yang menginginkan bukan perempuan, tetapi jelas untuk memenuhi kebutuhan laki-laki yang ingin sekedar ‘cuci mata’ hingga mengajak perempuan-perempuan SPG yang mau diajak kencan itu.
Inilah masyarakat yang tidak adil dan bias gender. Kebutuhan laki-laki untuk selingkuh dan serong—baik dengan perempuan pelacur kelas bawah maupun kelas atas—difasilitasi. Untuk perempuan tidak difasilitasi, karena hanya laki-lakilah yang seakan wajar jika “berzina”—sementara perempuan yang ingin cerai karena memang tidak betah dengan hubungan yang menindas dan tak berkualitas dalam pernikahannya, ia tak boleh cerai tanpa persetujuan si suami. Dan ketika se perempuan ketahuan lebih memilih laki-laki lain yang memang dicintainya, maka ia disebut perempuan “gatal” atau tidak pantas melakukan hal itu. Seakan mendua bagi laki-laki dianggap wajar, sementara perempuan yang tak pernah mendua dan lebih memilih dianggap terkutuk.
Kebutuhan laki-laki untuk selingkuh dengan kilat dapat difasilitasi di hotel-hotel, massage/panti pijat, bar-bar, night club, barber shop, salon-salon, billiard center, dan lokasi-likasi lain. Langganannya adalah pria dan bukan wanita. Hotel-hotel juga memfasilitasi laki-laki yang selingkuh dengan perempuan non-pelacur dengan tidak menanyakan surat nikah ketika sepasang laki-laki perempuan check-in. Dan memang kebanyakan bisnis hotel memang mengandalkan pada konsumen yang berupa pasangan tidak sah menurut agama ini.
Maka dari kisah di atas saya sebenarnya ingin menegaskan tesis yang tak terbantahkan bahwa lebih banyak laki-laki yang curang, serong, dan selingkuh daripada perempuan. Kenapa? Karena kondisi masyarakat yang bias-gender memfasilitasi dan mendukung laki-laki untuk serong, baik dari sudut pandang agama (poligami) maupun budaya, hingga dilihat dari aspek sosio-ekonomi.
***
[1] Sherry Argov. Why Men Marry Bitches?: Panduan Bagi Perempuan untuk Memenangkan Hati Pria.
[2] Sherry Argov. Why Men Marry Bitches?: Panduan Bagi Perempuan untuk Memenangkan Hati Pria.